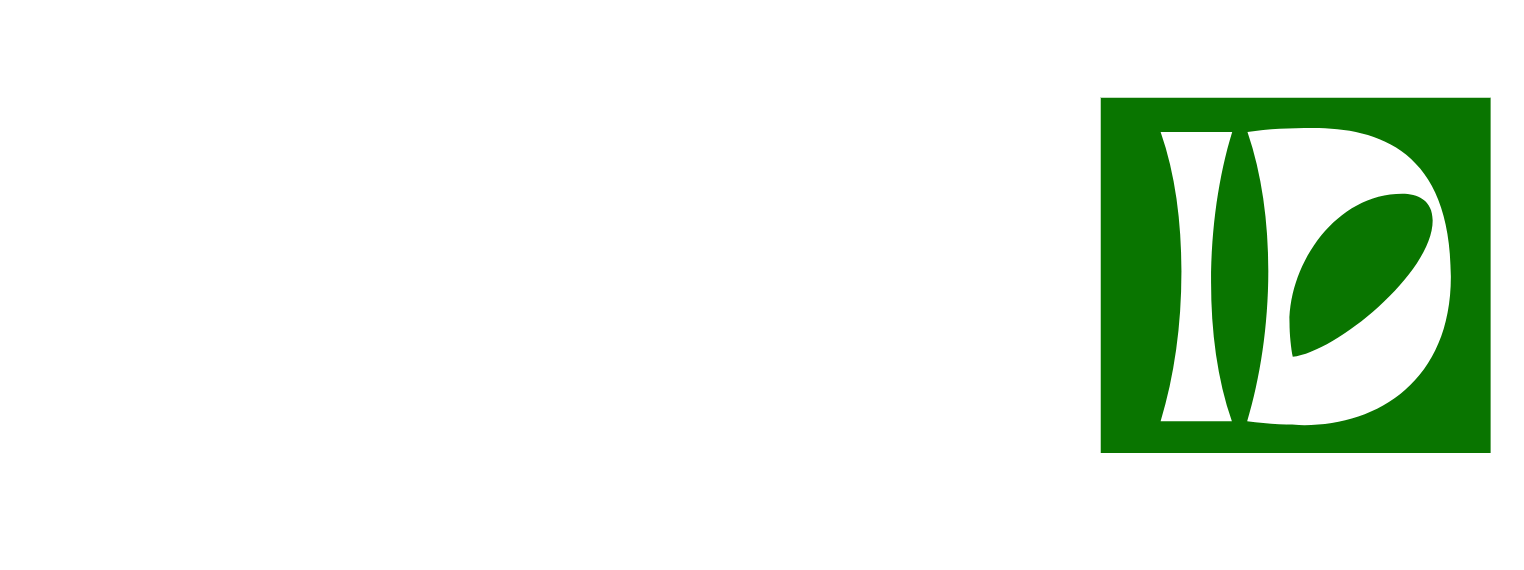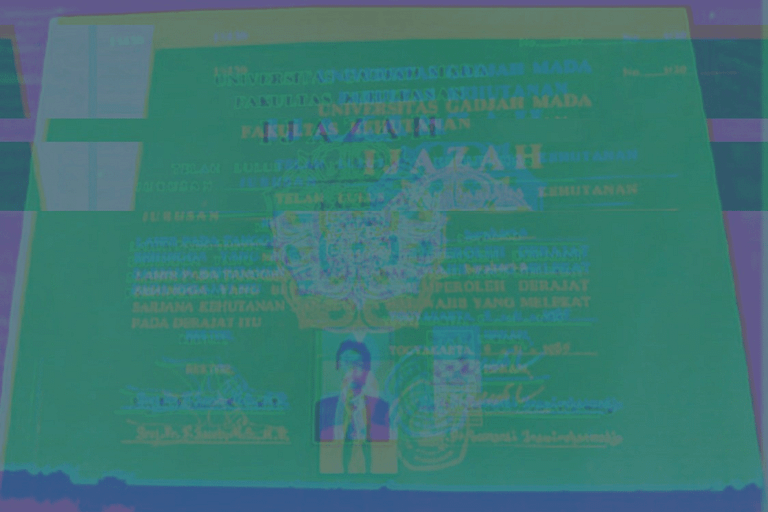Di negeri yang aroma kopinya memabukkan dan debat warungnya lebih pedas dari sambal ulek ibu kos, ijazah bisa menjadi lebih panas daripada panci ramen yang lupa diangkat. Begitulah kisah ijazah Presiden Joko Widodo, yang lebih sering diseret ke panggung publik ketimbang diabadikan dalam pigura keluarga.
Sejak pertama kali masuk ke arena politik nasional, Jokowi—yang lebih dikenal rakyat sebagai mantan wali kota, mantan gubernur, dan sekarang mantan tukang blusukan—tak pernah benar-benar lepas dari tuduhan bahwa ijazahnya fiktif. Isu itu bukan seperti angin lalu. Ia seperti bau rendang basi di kantin kampus: samar, mengganggu, tapi tetap membuat orang ingin tahu.
Jokowi, dalam berbagai kesempatan, menyampaikan dengan wajah datar dan nada jengah bahwa dirinya adalah alumnus Universitas Gadjah Mada. Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Hasil Hutan, angkatan 1980, lulus 1985. Tidak ada kejutan di sana, setidaknya bagi mereka yang percaya pada angka dan dokumen. Tapi, bagi sebagian kalangan, ijazah Jokowi bukan sekadar lembaran kertas bersegel; ia adalah simbol kekuasaan yang patut dicurigai, diperiksa, bahkan dibongkar.
Narasi tentang ijazah palsu tak datang dari sembarang penjuru. Ia menyeruak dari mulut para pegiat hukum, aktivis, hingga mantan politisi yang sepertinya rindu disorot kamera. Mereka menyusun berkas, menggugat ke pengadilan, dan menuntut pembuktian keabsahan. Lucunya, mereka tak menggugat kampus atau dosen yang katanya menerbitkan ijazah palsu itu. Mereka langsung menyasar Presiden. Mungkin karena kalau langsung ke UGM, risikonya hanya ditertawakan petugas arsip.
Kampus sendiri, tentu saja, merespons dengan gaya akademisi: datar, penuh referensi, dan tanpa tanda seru. Rektor UGM menyatakan dengan gamblang bahwa Jokowi memang mahasiswa mereka, bahkan menyebutkan nama dosen pembimbingnya. Tapi siapa peduli pada kesaksian institusi pendidikan jika ada spekulasi di YouTube yang lebih meyakinkan?
Kita hidup di zaman di mana kredibilitas seorang profesor bisa dikalahkan oleh narasi viral berdurasi 17 menit, diiringi musik latar mencekam dan font merah menyala. Di situ, ijazah Jokowi menjadi komoditas opini, bahan diskusi, dan—tentu saja—konten yang menjanjikan engagement tinggi.
Lucunya, publik yang menonton video-video itu tak pernah menuntut ijazah politisi lain. Tak ada yang minta ijazah Syahrul Yasin Limpo, tak juga Nadiem Makarim. Seolah-olah, keabsahan seseorang baru diuji ketika ia menjadi terlalu populer atau terlalu berkuasa.
Dalam drama ijazah ini, Jokowi seperti tokoh utama film noir. Ia tak banyak bicara, matanya lelah, dan dikelilingi karakter-karakter yang entah ingin membantunya atau menjatuhkannya. Ia pernah menyindir, dalam sebuah wawancara, bahwa ia sampai ingin menanyakan pada ibunya: apakah benar dirinya kuliah? Humor getir itu disambut tawa ringan, tapi tak meredam suara nyaring yang menuduh.
Ada sesuatu yang absurd di balik tuduhan ini. Sebab jika benar Jokowi tidak kuliah, maka ia berhasil membangun citra sebagai lulusan UGM selama hampir empat dekade. Ia menipu ribuan dosen, teman kuliah, wartawan, bahkan sistem verifikasi birokrasi yang sangat suka stempel. Jika benar demikian, maka Jokowi bukan hanya penipu, ia jenius konspirasi kelas dunia. Dan kita, rakyatnya, telah ditipu dengan sangat elegan.
Namun, bila tuduhan itu tidak benar, maka kampanye “ijazah palsu” adalah bagian dari pembusukan politik yang paling malas: menggugat bukan untuk membuktikan kebenaran, tetapi untuk merusak persepsi.
Tentu, setiap warga negara berhak menggugat. Tapi ada perbedaan antara menggugat demi keadilan dan menggugat demi konten. Yang pertama mungkin membawa perubahan, yang kedua hanya membawa viewer.
Sayangnya, institusi hukum kita terkadang terlalu ramah pada gugatan absurd. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat menerima gugatan terhadap ijazah Jokowi. Walau akhirnya gugatan itu ditolak, ruang sudah dibuka untuk spekulasi. Persidangan berjalan, media meliput, dan para penganut teori konspirasi berpesta.
Media sosial, seperti biasa, menjadi ladang subur bagi kebingungan kolektif. Netizen menggelar “investigasi digital”, menyoroti foto-foto lama, membandingkan tulisan tangan, bahkan mengaitkan kode ijazah dengan kalender Jawa. Setiap orang tiba-tiba menjadi ahli forensik dokumen. Lucunya, sebagian dari mereka mungkin tidak tahu bentuk ijazah kampus mereka sendiri.
Ada juga kelompok yang mengaitkan tuduhan ini dengan politik identitas. Mereka berpendapat bahwa Jokowi, yang datang dari Solo dan bukan bagian dari elit tradisional, tak pantas memegang kekuasaan sebesar itu. Maka, narasi ijazah palsu adalah cara paling murah untuk meruntuhkan legitimasi tanpa perlu debat panjang.
Lantas, bagaimana reaksi publik secara umum? Mayoritas tetap diam, melanjutkan hidup, dan menganggap isu ini seperti sinetron stripping: ada terus tapi tidak penting. Mereka tahu bahwa mempermasalahkan ijazah seorang presiden di tahun terakhir masa jabatannya lebih banyak menimbulkan lelah ketimbang manfaat.
Sementara itu, di kampus UGM, arsip tetap tersimpan rapi. Petugas perpustakaan tetap bekerja, tak peduli berapa banyak vlog yang menuduh mereka bagian dari konspirasi. Bagi mereka, kebenaran bukanlah sesuatu yang perlu dipertontonkan tiap hari. Ia cukup disimpan, diverifikasi, dan siap dikeluarkan jika negara benar-benar memerlukannya.
Dan Jokowi? Ia tetap bekerja, setidaknya secara administratif. Negara ini masih berjalan, dengan segala kekacauan, keberhasilan, dan polemiknya. Ia telah melewati dua pemilu nasional, dua debat capres, dan ratusan demonstrasi. Tapi selembar ijazah, entah mengapa, masih menjadi momok yang lebih menakutkan ketimbang inflasi atau kerusakan lingkungan.
Narasi tentang ijazah Jokowi mungkin tak akan mati. Ia akan terus hidup sebagai dongeng politik modern, diceritakan dari satu akun YouTube ke akun Facebook, diselingi analisis ngawur dan potongan video hitam putih.
Tapi sejarah tak ditulis oleh algoritma. Ia ditulis oleh data, arsip, dan—jika kita cukup beruntung—oleh orang-orang yang masih percaya bahwa satu kebenaran lebih berharga dari seribu opini.
Dan jika kelak, dua puluh tahun dari sekarang, generasi muda menanyakan, “Kenapa dulu kita ribut soal ijazah presiden?” barangkali jawabannya adalah: karena di negeri ini, kita lebih percaya pada fitnah yang menyenangkan daripada fakta yang membosankan.