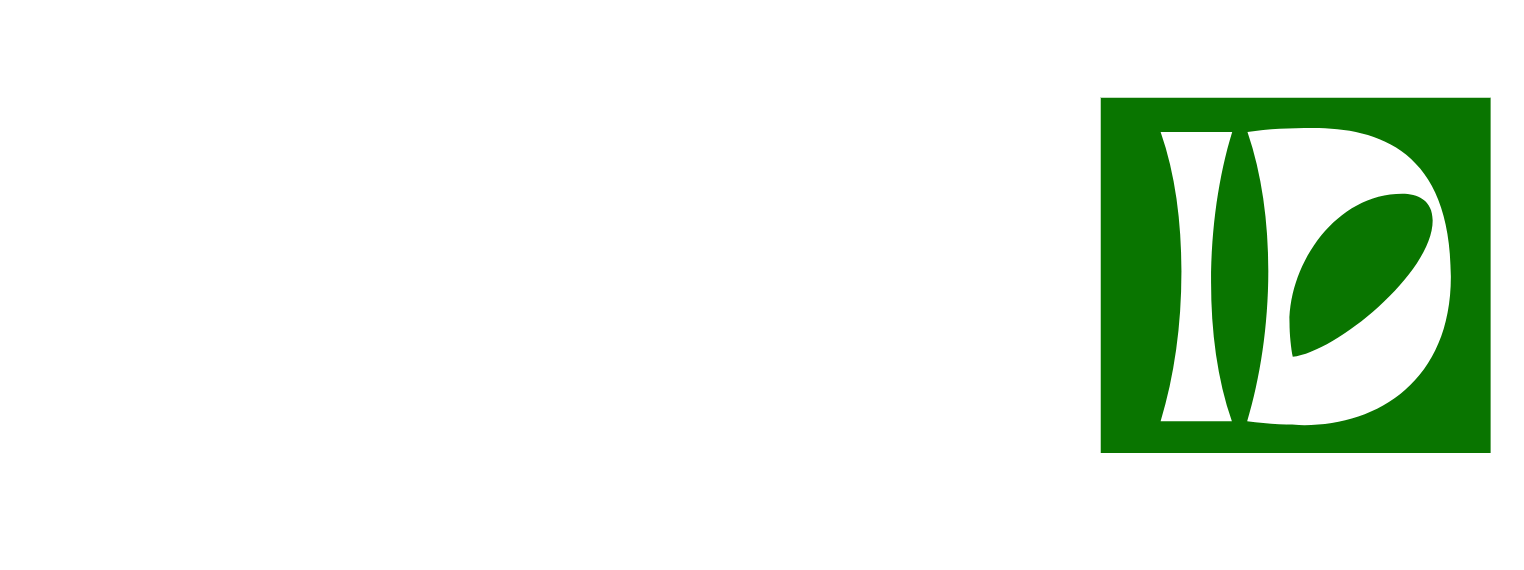Di tengah embusan angin Embung Wisata Sungai Abu, Tabek Gadang, Nagari Toboh Gadang, Padang Pariaman, panorama tak lagi hanya soal alam. Yang tersaji kini adalah dentuman. Bukan dentuman gunung berapi, tentu saja—Sumatera Barat sudah cukup sabar menghadapi yang satu itu. Ini dentuman lain: deretan speaker raksasa yang berteriak dalam nada-nada minor dan mayor dari sebuah ajang bernama Festival Soundbar. Lomba orgen tunggal, yang anehnya… sudah tidak lagi tunggal.
“Ada Yang Unik Di Padang Pariaman Saat Ini. Lomba Orgen ‘Festival Soundbar’. Banyak orgen mengikuti. Lomba ini diikuti sekitar 17 sound dari berbagai daerah di Sumatera Barat, ada yang dari Jambi,” tulis Afrizal Chan dalam sebuah unggahan Facebook.
Dalam video yang ia bagikan, tampak barisan “sound” — bukan musisi, bukan penyanyi — melenggang seperti rombongan calon pengantin: penuh percaya diri, gagah, dan tentu saja… nyaring. Festival ini, kata Afrizal, mirip-mirip Karnaval Sound Horeg yang lebih dulu tenar di Jawa Timur. Dan benar saja, salah satu akun Instagram media lokal Padang langsung ikut membagikan video itu sambil bertanya kepada warganet, “Baa manuruik sanak?”
Pertanyaan itu, sesungguhnya, bisa ditarik lebih jauh: “Ini semua mau ke mana?”
Meniru yang Viral, Melupakan yang Bernilai
Mari kita berkaca pada Jawa Timur. Karnaval Sound Horeg di sana telah menjelma jadi tontonan jalanan: truk raksasa membawa speaker berukuran nyaris menyaingi gergasi, musik EDM atau dangdut remix diputar dalam volume yang tidak disarankan oleh WHO, dan ibu-ibu hingga anak-anak ikut berjoget dengan bebas di jalanan.
Namun populernya tak sebanding dengan persoalannya. Salah satu gapura masjid, misalnya, pernah dirobohkan hanya agar truk sound bisa lewat. Bukan satire. Fakta.
Lalu ada aksi joget—vulgar, kata sebagian—yang dilakukan secara massal oleh para remaja, ibu-ibu, hingga balita yang belum fasih bicara. Jika dulu anak-anak meniru gerakan randai, kini mereka menirukan goyang TikTok di tengah jalan lintas. MUI Jawa Timur bahkan telah mengeluarkan fatwa larangan terhadap praktik joget vulgar di acara seperti ini. Tapi seperti kebanyakan fatwa: ia hanya nyaring di ruang rapat, tapi tenggelam di lapangan, dikalahkan volume amplifier.
“Hiburan rakyat kok diharamkan?” seru sebagian warganet. Sebuah kalimat yang menandai zaman: ketika hiburan, betapa pun bising dan tak bernilai, dianggap hak dasar—lebih penting dari akhlak, bahkan kesehatan.
Padang Pariaman dan Kesedihan yang Disenyapkan
Sementara itu, di Padang Pariaman, orgen tunggal tak ingin ketinggalan. Mereka tampaknya ingin turut serta dalam arus viral: dari Jawa Timur ke TikTok, dari TikTok ke nagari.
“Kenapa mesti meniru yang gaduh dan tak berfaedah?” tanya segelintir warga, diam-diam.
Padahal Padang Pariaman tidak kekurangan budaya. Ada Tambua Tasa yang menggetarkan jiwa, bukan hanya gendang. Ada Randai yang menyampaikan nilai melalui lakon. Ada Silek yang mengajarkan disiplin, bukan hanya lenggokan pinggul. Tapi mungkin budaya ini terlalu lirih dibandingkan ledakan 18-inch woofer.
Orang Minang, yang konon dikenal karena adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, kini mulai ikut-ikutan lomba siapa paling nyaring. Tidak jelas apakah demi kebudayaan atau sekadar demi viewer Instagram Story.
Fenomena Soundbar dan Sound Horeg menunjukkan satu hal: suara kini bukan lagi alat komunikasi, tapi senjata dominasi. Di tengah masyarakat yang makin terpolarisasi, suara yang paling keras kerap dianggap paling benar. Mereka yang berbicara dengan santun dan lambat dianggap “ketinggalan zaman”. Mereka yang mengingatkan malah dituduh “tidak gaul”.
Lalu, di mana batasnya?
Apakah harus menunggu telinga rusak atau akhlak remuk baru kita sadar bahwa tidak semua yang ramai itu baik? Bahwa tidak semua yang memekakkan itu bentuk ekspresi yang sehat?
Atau kita memang sedang menuju era baru, di mana speaker 18-inch lebih dipercaya daripada suara tetua?