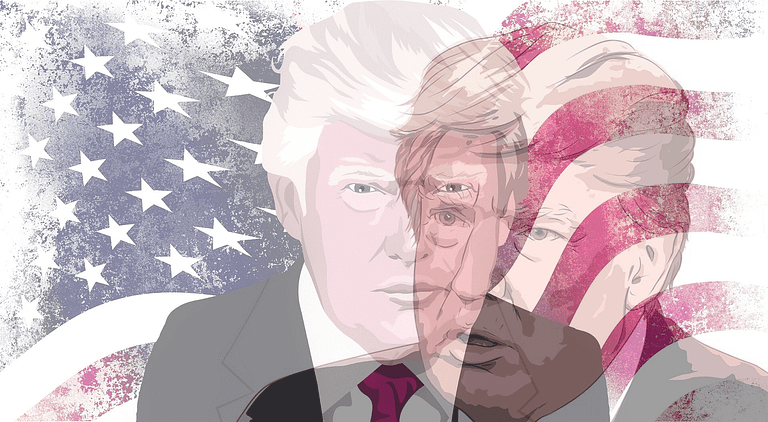Seloka.id – Enam bulan sudah Donald Trump kembali menduduki singgasana Gedung Putih, dan bangsa yang pernah disebut laboratorium demokrasi kini menjelma arena pertunjukan ilusi. Seperti opera sabun yang ditulis oleh algoritma partisan, cerita ini terus bergulir: dramatis, menggelikan, kadang-kadang menyeramkan.
Jaclyn Taylor dari Iowa—seorang pengusaha wanita yang memuja Trump layaknya nabi pemasaran—memberi nilai 9 dari 10 untuk semester pertama sang presiden. Ia menyebut “kemajuan yang tak tertandingi,” seolah kebijakan Trump mampu membuat harga bensin lebih jinak dari kucing Persia.
Lawrence Malinconico, profesor dari Pennsylvania yang namanya terlalu akademis untuk pemilu Amerika, menimpali dari ujung yang berseberangan. “Nol,” katanya. “Trump telah menempatkan orang-orang tidak kompeten ke posisi berkuasa.” Dalam kosakata akademik, itu mungkin berarti “bencana birokrasi sistemik.”
Dari New Hampshire hingga Michigan, para pemilih Trump bersorak: “Biaya hidup turun!” sementara oposisi berteriak, “Negara ini runtuh!” Tak ada tengah-tengah; hanya lubang hitam opini yang memutar semua logika dan statistik ke arah preferensi masing-masing.
Satu hal yang menyatukan mereka? Jeffrey Epstein. Isu yang dulu menjadi alat retoris Trump untuk menuduh Partai Demokrat, kini seperti bumerang plastik murah yang kembali menghantam kepala sendiri. Bahkan pendukung setia pun mulai bertanya, “Apa yang berubah?” Nada sang Presiden berubah dari heroik menjadi hening. Transparansi dijanjikan, lalu ditelan senyap.
Rachal Kulak dari Virginia, seorang Kristen konservatif, menyebutnya “bencana berkas Epstein.” Tapi tetap, cintanya pada Trump tak berkurang. Bahkan ketika disodor teori konspirasi bahwa semua ini ada kaitannya dengan Israel—sebuah pendapat yang lebih cocok untuk forum daring beraroma teori Flat Earth—dukungan tetap mengalir.
Kita pun bertanya: apakah Trump benar-benar presiden, atau sekadar karakter utama dalam serial Netflix yang belum rampung ditulis?
Sementara itu, masalah hidup nyata seperti biaya sewa, harga makanan, dan kemiskinan yang semakin gaya—alias middle class yang hidup dari paylater—tetap jadi momok.
Dan kini, setelah enam bulan menghidupi negeri dari balik podium dan utas Twitter (eh, maksud kami Truth Social), Trump mendapati satu masalah yang bahkan tidak bisa dia bangun tembok di sekelilingnya: Jeffrey Epstein.
Skandal lama yang dulu digunakan untuk menyerang lawan kini seperti daging beku dalam microwave: meleleh, bocor, dan mengeluarkan bau yang sulit dijelaskan.
Pendukung Trump yang biasanya lebih setia daripada para penggemar K-Pop, kini mulai melirik kiri dan kanan. Pete Burdett dari New Hampshire, misalnya, menulis dengan gaya Shakespeare modern: “TIDAK YAKIN saat ini.” Sebuah komentar yang bisa berarti apa saja—dari skeptis halus sampai krisis eksistensial politik.
Rachal Kulak dari Virginia, yang biasanya menyebut nama Tuhan dan Trump dalam satu tarikan napas, kini mengaku bahwa “berkas Epstein” terasa seperti luka lama yang ditempel plester basah. Tapi tentu saja, cintanya tak goyah. Karena dalam cinta politik, kebohongan kecil adalah bagian dari romansa.
Di sisi lain, para Demokrat seperti Joan London, pengacara dari Pennsylvania yang dulu pendukung Reagan, kini lebih cocok jadi pengamat true crime. Baginya, ketertutupan Trump dalam kasus Epstein bukan sekadar politik, tapi thriller konspirasi tanpa sutradara.
“Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa panik?” tanya London. Pertanyaan yang sama yang biasanya diajukan ibu-ibu saat anaknya menolak membuka isi tas sekolah.
Sementara itu, harga sewa melonjak, gaji tetap stagnan, dan kelas menengah mulai terlihat seperti mitos urban. Cynthia Sabatini, seorang Republikan suburban, menyatakan dengan jujur, “Tarif bukanlah pendekatan yang baik.” Itu adalah cara elegan mengatakan: “Kami dijual mahal oleh pria yang katanya paham bisnis.”
Lalu ada Kim Cavaliere, independen dari Georgia, yang merasa standar hidupnya “turun” sejak Trump kembali berkuasa. Menurutnya, kebijakan Trump hanya untuk orang kaya. Dan ketika ditanya soal harapannya, ia menjawab, “Saya harap bisa menebak nomor lotre saya seperti saya menebak Elon Musk dan Trump bakal putus hubungan dalam setahun.” Humor: satu-satunya yang tersisa dari demokrasi.
Disclaimer
Artikel ini merupakan hasil pengolahan ulang dan narasi interpretatif dari informasi publik dan laporan jurnalistik internasional, termasuk CNN. Semua nama, kutipan, dan konteks diproduksi ulang dalam gaya khas Seloka — satire naratif yang menggigit namun tetap berakar pada fakta. Kami tidak bermaksud menggantikan laporan asli atau menyalinnya secara literal. Jika Anda mencari jurnalisme lurus tanpa bumbu, Anda salah alamat.